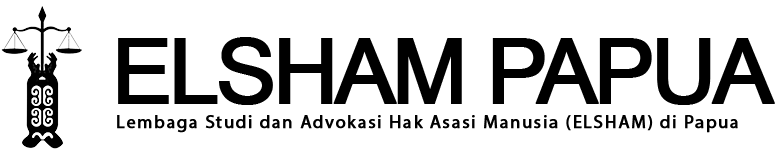Oleh Fred Benu
Bersamaan dengan Presiden Soekarno mengumumkan Operasi Trikora di Tanah Papua pada 1961, banyak pihak khususnya orang Papua berteriak menuntut konsesi politik akan adanya kemerdekaan bagi Papua. Tuntutan politik ini terus berlanjut sampai Pemerintah Indonesia meresponsnya dengan pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) pada 22 Oktober 2001.
Lahirnya UU ini sedikit mereduksi tuntutan politik sebagian besar orang Papua, walaupun UU ini tetap ditolak oleh sebagian orang Papua. Papua berada di bawah bayang-bayang “hujan berkat” perhatian Pemerintah Pusat dengan pengucuran dana Otsus yang terus meningkat dari sekitar Rp 3, 5 miliar 2001 menjadi Rp 4,5 triliun 2006 dan terakhir tercatat Rp 21 triliun.
Pasal 34 ayat (3) UU Otsus telah mewajibkan komitmen anggaran untuk pelaksanaan Otsus sebesar 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Komitmen politik pemerintah yang diikuti oleh komitmen bujet sejak 2001 sedikit dapat menekan gojolak politik di Tanah Papua.
Setelah tujuh tahun pemberlakuan Otsus, pertanyaan beralih ke, apakah benar “hujan berkat” telah benar-benar “tercurah” bagi akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan? Jawaban yang patut disampaikan, belum terwujud, bahkan sangat mungkin persoalannya menjadi bertambah runyam.
Tuntutan politik yang semula dapat diredam melalui “sajian” otonomi di atas Tanah Papua ternyata tidak pernah dinikmati secara bersama. Padahal, semua anak Papua “menyusui” pada “bunda” yang sama – Tanah Papua- yang memberikan kelimpahan sumber daya alam dan kebebasan untuk dinikmati secara bersama. Tapi, saat ini Tanah Papua harus menyaksikan sebagian anak-anaknya yang kebetulan mendapat akses untuk duduk dekat “meja otonomi” menikmati sambil menari atas kebaikan hati Pemerintah Pusat. Sedangkan mereka yang lain tetap menonton “pesta otonomi” dalam kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.
Kedamaian pun semakin jauh dari Tanah Papua dan isu beralih ke persoalan sosial, seperti: korupsi, ketidakadilan, dan pemborosan. Tuntutan politik kembali disuarakan oleh sejumlah mahasiswa di jalan-jalan di Kota Jayapura, Semarang, Makassar, Jakarta, dan lainnya. Tuntutan bagi diadakannya referendum untuk menentukan nasib Tanah Papua. Semua karena keadilan dan kesejahteraan tak kunjung tiba. Otonomi yang menjanjikan keadilan dan kesejahteraan malah berbuah ketidak-adilan dan kesenjangan sosial-ekonomi di antara orang Papua.
Indikasi Ketidakadilan
Saya bukan putra asli Papua, tapi tahun ini adalah tahun ketiga bagi saya menjelajahi Tanah Papua mulai dari Port Numbai, kemudian Wamena di Pegunungan Tengah, sampai Bovendigoel dan Pantai Kasuari di selatan, untuk mengevaluasi program pembangunan masyarakat bersama World Vision International. Pengamatan saya di sejumlah daerah pedalaman membawa saya pada suatu pemahaman tentang mengapa orang Papua sangat keras menyuarakan keadilan dan bahkan sampai pada tuntutan referendum.
Saya tidak ingin melakukan generalisasi bagi seluruh Papua, tapi marilah kita belajar dari beberapa kasus yang dapat dijadikan indikasi ketidakadilan. Saya pernah menginap di salah satu hotel di Kota Wamena. Lalu datang seorang bupati di daerah Pegunungan Tengah untuk menginap di hotel yang sama. Saya terheran-heran ketika melihat bupati ini memberikan tip Rp 50 juta bagi pemilik hotel yang hanya membantu memindahkan koper sang bupati. Kemudian diikuti dengan pembagian amplop bagi sejumlah orang yang datang mengunjunginya.
Saya bertanya dalam hati berapa banyak uang rakyat – uang otonomi khusus- yang dihambur-hamburkan dengan cara seperti ini.
Di hotel yang sama, saya menemukan seorang anggota DPRD yang baru saja terpilih dan kemudian memboyong seluruh anggota keluarganya untuk tinggal di hotel selama berbulan-bulan. Sang anggota dewan ini enggan untuk tinggal di rumahnya seiring dengan peningkatan status sosialnya. Padahal di hotel yang sama saya juga menemukan sejumlah penduduk asli, yang setiap hari duduk di halaman hotel dan terkadang masuk ke ruang lobi, untuk menjajakan anyaman noken, kalung, dan kampak batu tanpa sehelai benang pun menutupi tubuh mereka kecuali “koteka”. Ini juga salah satu indikasi ketidakadilan sebagai buah pemberlakuan Otsus.
Saya juga mengamati bahwa hampir seluruh bupati memiliki kebijakan untuk membeli pesawat sendiri bagi daerahnya, bahkan ada yang bermesin jet guna mendukung kelancaran tugas pemerintahan. Bahkan ada bupati yang mampu membeli pesawat jenis Antonov sekalian dengan pilotnya dari Rusia dengan alasan melayani tugas pemerintahan dan tugas-tugas pelayanan masyarakat.
Lantas bandingkan dengan situasi pendidikan di sejumlah daerah pedalaman. Satu SD yang terletak hanya beberapa kilometer dari Wamena dengan enam kelas hanya dilayani oleh dua guru. Saat ditanya tentang keberadaan guru yang lain ternyata mereka lebih sering tinggal di Wamena. Hanya sekali dalam satu atau dua bulan mengunjungi sekolahnya. Aktivitas anak-anak di kelas 5 dan 6 SD tidak bedanya dengan mereka pada jenjang play group.
Saya terus melihat situasi di Kota Merauke. Kota ini memiliki dinamika ekonomi yang cukup baik, tapi sulit untuk menemukan orang asli Papua di kota ini. Sebagian besar penduduk asli Papua telah bergeser ke daerah-daerah pedalaman yang dikelilingi oleh hutan lebat.
Masalah Kesehatan
Belum lagi masalah kesehatan dasar penduduk yang masih sangat memprihatinkan karena soal diare, gizi buruk, kebutuhan air bersih, ketiadaan fasilitas MCK, AIDS, dan lain-lain. Saya dapat dengan mudah mengamati situasi yang sangat kontras antara sebagian besar penduduk pendatang yang mengokupasi daerah urban di sejumlah kota di Papua dengan sebagian besar orang Papua yang tinggal di kawasan terpencil.
Banyak pihak yang justru menyalahkan situasi yang terjadi karena Otsus dan menghendaki agar dihentikan. Bahkan almarhum Theys Eluay pernah berujar bahwa ia mendapat mandat dari rakyat Papua untuk meluruskan sejarah Papua bagi kemerdekaan, bukan untuk menerima Otsus. Tapi, bukankah Otsus ini juga yang pernah dikehendaki oleh banyak pihak termasuk sejumlah orang Papua? Atau mungkin terlalu cepat Jakarta merespons tanpa disertai dengan suatu kajian sosial-politik yang mendalam?
Cerita kegagalan Otsus karena kurangnya persiapan masyarakat maupun institusi pada tingkat supra-struktur adalah salah satu simpul keruwetan yang menyebabkan harga perdamaian di Tanah Papua terasa begitu mahal. Simpul lainnya terletak pada diri orang Papua sendiri. Selagi ada ketulusan untuk menyelesaikan persoalan demi membangun suatu kedamaian di Tanah Papua, maka pasti misi mulia ini menemukan jalan keluar. Tapi, selama mindset sebagian anak Papua hanya terpaut pada kata “merdeka” maka alternatif solusi apa pun menjadi tidak berarti.
Penjelajahan saya di Tanah Papua menemukan indikasi seperti yang dikhawatirkan, mulai dari sejumlah elite pemerintahan, kalangan akademisi, sampai sebagian orang Papua di Distrik Mindiptana, Kabupaten Bovendigoel (perbatasan PNG). Perdamaian akan tetap berharga mahal tidak saja bagi orang Papua, tapi bagi Bangsa Indonesia.
Pada saat yang sama kita, yang bukan orang Papua, memandang Otsus dalam suatu perspektif “optimisme irasional”. Rasionalisasi empirik saya mengatakan mungkin kita harus membuat kalkulasi politik ulang bahwa dalam kurun waktu kurang dari 50 tahun Papua masih merupakan bagian dari NKRI.
Masih ada suatu simpul keruwetan lain yang perlu dipahami oleh orang Papua sebagai bagian dari NKRI. Bahwa perjuangan akan lahirnya perdamaian di Tanah Papua tidak akan berakhir dengan dilakukannya referendum untuk menentukan nasib sendiri (jika itu dimungkinkan). Karena mungkin saja cerita tentang kesulitan yang menjurus pada kegagalam membangun suatu bangsa (failed nation) di Timor Timur akan terjadi di Tanah Papua. Bukankah di antara orang Papua sendiri masih ditemui banyak perbedaan prinsip perjuangan antarberbagai kelompok?
Saat ini diperlukan ketulusan hati dari semua anak Papua untuk duduk bersama dengan kepala dingin, bahkan berjiwa besar, untuk menghadirkan pihak lain, khususnya pemerintah Jakarta, guna menemukan solusi terbaik. Suatu solusi dengan biaya sosial-politik paling minim dalam menghadirkan perdamaian di Tanah Papua. Jangan ada lagi yang mengatakan bahwa “perdamaian di Tanah Papua berharga mahal”.
Penulis adalah dosen Universitas Nusa Cendana, Kupang
Source: Suara pembaruan